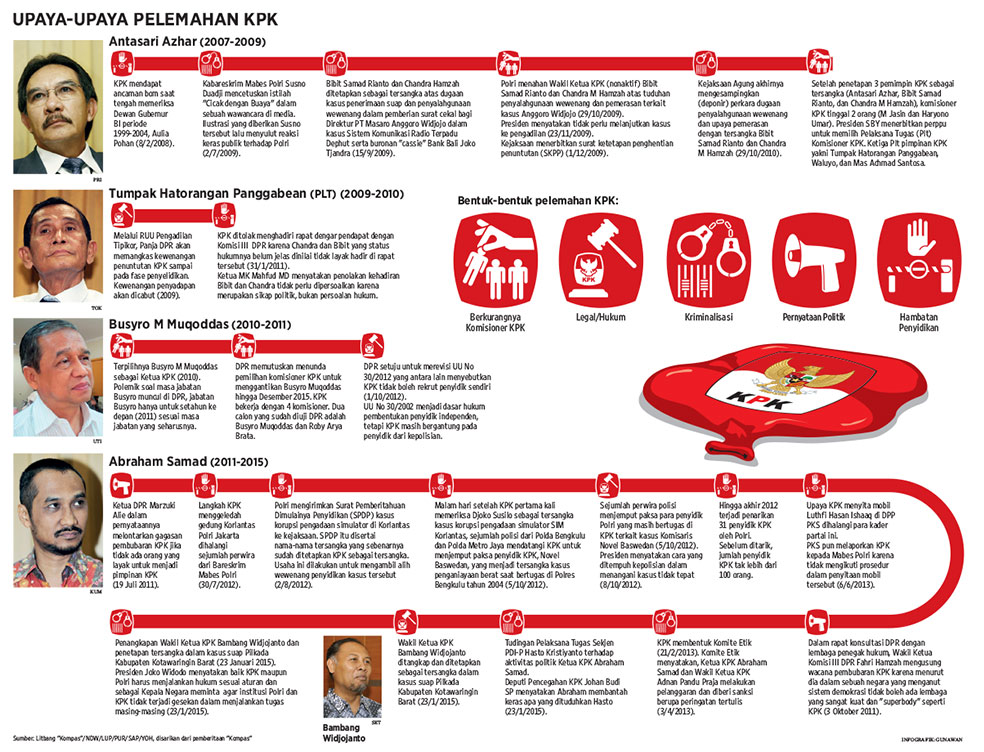PILIHAN Presiden Joko Widodo menjadikan Badrodin Haiti, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mendatangkan banyak catatan.
Ada apresiasi, tetapi ada juga sejumlah pertanyaan besar mengiringi. Konsekuensi yang memang harus diterima karena langkah yang diambil sebelumnya memang kurang pas.
Presiden telah memilih mengajukan secara tunggal Budi Gunawan (BG), sosok yang kemudian terbukti ada masalah. Ada kesempatan untuk menarik pencalonan ini, tetapi tidak dilakukan Presiden. Situasi ini semakin sengkarut akibat cara DPR memperlakukan usulan ini. Logikanya, DPR harus menjadi pihak yang mengingatkan dalam kapasitas sebagai pengawas eksekutif. Namun, walau telah ditetapkan sebagai tersangka, DPR tetap menyatakan BG fit dan proper untuk diangkat menjadi Kapolri. Padahal, dengan menjadi tersangka di KPK, yang berarti akan menjadi pesakitan di pengadilan, sudah mengindikasikan ketidaklayakan seseorang sebagai Kapolri.
Mencari solusi
Posisi sudah saling mengunci saat ini. Dengan ”mengambangkan” pengangkatan BG, pada hakikatnya Presiden berseberangan dengan apa yang diinginkan DPR. Namun, pada saat yang sama, ada banyak pertanyaan, termasuk sampai kapan BG diambangkan? Sampai kapan Wakapolri menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri? Tahapan awal yang dilakukan Presiden dan DPR seakan-akan sudah selesai.
Tak mungkin lagi Presiden menolak. Dia dihadapkan pada pilihan sulit. Setidaknya, ada dua pilihan yang berseberangan secara diametral yang dihadapi Jokowi. Pertama, tak melanjutkan pencalonan BG. Dengan tidak melanjutkan pencalonan BG, ada banyak pilihan jalan yang tersaji, tetapi akan mendatangkan konsekuensi berbeda.
Misalnya, tetap mengambangkan BG dan memilih melanjutkan Badrodin sebagai Plt Kapolri. Namun, ini tentu saja jauh dari ideal karena banyaknya kerja-kerja Kapolri yang harus diambil dalam kapasitas Kapolri dan bukan selaku Plt yang memang pada hakikatnya memiliki keterbatasan bertindak atas nama Kapolri. Artinya, pada langkah pertama ini Presiden lebih baik memilih menguatkan moral dan etika publik dengan tak melantik BG, lalu mengajukan calon baru dengan menggunakan mekanisme Pasal 11 Ayat 1 dan 2 yang kemudian kembali ke proses persetujuan di DPR.
Sesungguhnya, pada langkah ini bukan hanya alasan etika yang menjadi pertimbangan. Ada fondasi ”kecil” hukum, yakni itikad Presiden mengisi dan menghindari stagnannya pemerintahan karena suatu kondisi. Tindakan ini semacam diskresi administratur sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tidak hanya itu, tindakan ini juga menegakkan prinsip penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN sebagaimana dikembangkan di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.
Namun, bukan berarti tanpa kritik. Langkah ini dapat dinilai beragam. Bisa dianggap ketidakpatuhan Jokowi atas UU Polri atau pembangkangan Presiden atas persetujuan yang telah dikeluarkan DPR. Namun, lewat langkah ini, Presiden akan mendapatkan dukungan moral publik yang lebih kuat.
Pilihan kedua, meneruskan pelantikan BG. Namun, setelah dilantik, demi menjaga semangat pemberantasan korupsi di publik, Presiden dapat langsung memberhentikannya dengan alasan-alasan yang memang dimungkinkan dalam penjelasan pasal-pasal di UU Polri. Presiden dapat memilih memberhentikan BG setelah pengangkatannya dengan mekanisme yang tersedia di dalam UU Polri.
Dalam hal ini, Presiden dapat langsung memberhentikan BG dengan pemberhentian definitif seperti diatur Pasal 11 Ayat 2 atau pemberhentian sementara seperti diatur Pasal 11 Ayat 5. Artinya, Presiden bisa memilih antara mengajukan Kapolri definitif baru sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat 1 dan 2 atau Plt Kapolri yang tunduk pada aturan Pasal 11 Ayat 5. Baik calon baru maupun Plt harus dikirimkan konfirmasinya ke DPR.
Langkah kedua ini lebih fit ke aturan hukum, tetapi sangat deras menggerus moral publik yang sedari awal menuntut negara tak boleh melantik pejabat negara yang melakukan korupsi. Di jalur ini, boleh jadi pertanyaan politiknya jauh lebih kecil, tetapi Presiden akan dihadapkan pada kritikan publik.
Pilihan antinomis
Pada titik inilah Presiden Jokowi harus memilih. Pilihan hukum, secara teoretis, memang sering memberikan nuansa membingungkan karena ada ”penyakit” hukum bernama antinomi. Antinomi adalah pertentangan yang mendera hukum karena adanya dua hal yang bertentangan, tetapi harus dijaga oleh hukum secara bersamaan. Moral publik yang dalam konsepsi hukum Grotius adalah sesuatu yang harus dijaga, tetapi pada saat yang sama kepastian hukum proses pelantikan telah disepakati Presiden dan DPR sebagaimana tertera di UU Polri.
Posisi pilihan yang tentunya tidak sederhana. Wolfgang Friedmann menyebutkan, pertentangan antinomi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terjadi sebagai akibat dari posisi alamiah hukum itu sendiri, yang berdiri di antara nalar filsafati dan kebutuhan praktis politik yang penat kepentingan. Dan, pada titik itulah Presiden harus segera mengambil langkah untuk tak memperpanjang debat publik yang sudah mulai ngawur dan melangkah terlalu jauh hingga ke isu impeachment.
Di sinilah kenegarawanan Presiden dibutuhkan. Ambillah langkah antara pilihan satu dan pilihan dua yang bisa jadi adalah simalakama, tetapi paling tidak menuju ke jawaban permasalahan. Apa pun langkah Presiden harus diikuti dengan tindakan penegas agar siapa pun di negeri ini paham dengan posisi Jokowi yang sesungguhnya dalam relasi penegakan hukum anti korupsi.
Baik pilihan pertama maupun kedua mendatangkan konsekuensi, Presiden akan memilih orang baru. Oleh karena itu, proses yang lebih baik dari ketika mencalontunggalkan BG harus dilakukan. Libatkan KPK, PPATK, dan lembaga penting lain. Presiden juga dapat mengingatkan institusi Polri agar tak melawan KPK secara kelembagaan. Melakukan pra-peradilan atas KPK secara kelembagaan tentu hal aneh mengingat tuduhan terhadap BG adalah individual dan bukan terhadap institusi Polri. UU Polri jelas menyatakan Polri berada di bawah Presiden. Dengan membiarkan Polri melakukan perlawanan institusional atas KPK hanya akan menampar muka Presiden Jokowi yang sejak awal telah menegaskan itikadnya untuk memperkuat penegakan hukum anti korupsi di negeri ini.
Catatan bagi siapa pun yang tidak menginginkan sengkarut ini berlanjut, sesungguhnya yang dibutuhkan adalah kenegarawanan kepada siapa pun yang terlibat di dalam sengkarut ini, termasuk untuk BG sendiri. Andai BG mau menegakkan etika publik bahwa siapa pun yang berstatus tersangka harus mau mundur dari jabatan dan pencalonan, sesungguhnya sebagian besar dari sengkarut ini akan selesai. Jika BG mundur, amat sangat meringankan posisi antinomis yang dihadapi Jokowi dan DPR yang terlibat dalam sengkarut ini. Presiden dan DPR harus duduk bersama. Polri juga harus menyadari pentingnya dorongan penyelesaian persoalan ini. Tindakan tak penting dan tidak pas hanya akan memperkeruh situasi.
Zainal Arifin Mochtar
Pengajar Ilmu Hukum dan Ketua Pukat Korupsi pada Fakultas Hukum UGM Yogyakarta